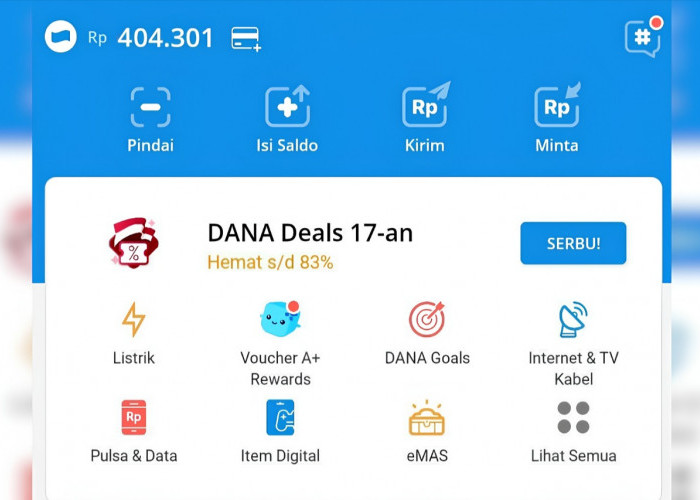Kakak Sofwati

Oleh: Dahlan Iskan NAMA-NAMA tempat ini terus terngiang di telinga. Sejak remaja: OKU, Komering, Martapura, Jagaraga, Palembang. Yang sering mengucapkannya orang luar Jawa pertama yang saya kenal: Husein Roni. Ia pacar kakak saya: Sofwati. Kakak nomor dua di empat bersaudara kami. Saya tidak tahu, tepatnya di kota yang mana Mas Husein lahir. Gak penting. Pokoknya, ia dari Sumatera. Bukan Jawa. Yang saya tahu: ia sedang kuliah di Universitas Islam Indonesia (UII) Cabang Madiun. Itu setelah ia tamat Pondok Modern Gontor Ponorogo. Mas Husein, kalau bicara, intonasi suaranya paling beda: logat luar Jawa. Ia bisa berbahasa Jawa, tapi pengucapannya kacau sekali. Itu saya ketahui ketika ia berkomunikasi dengan ayah saya yang hanya bisa lancar berbahasa Jawa. Yang sering diomongkan orang-orang di desa saya: Mas Husein selalu membawa badik yang ia slempitkan di pinggang. Seperti selalu siap berkelahi. ”Pak Husein itu takut apa ya kok selalu bawa pisau.”Begitu rerasan orang di desa saya. Mereka tidak tahu, itulah kebiasaan orang suku Komering zaman itu. Selama kuliah, Mas Husein aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Belakangan saya tahu ia menjabat ketua HMI Cabang Madiun. Rupanya, di HMI itulah ia mengenal kakak saya –yang juga aktivis HMI. Kakak saya itu, rasanya, ketua Korps HMI-Wati (Kohati) Jawa Timur. Dari kelompok liberal. Kakak sering dipanggil sebagai ”agen Nurcholish Madjid di Jatim”. Artinya: dia ikut dalam gerakan pembaharuan pemikiran Islam yang diprakarsai Cak Nur itu. Saya memanggil pacar kakak saya itu dengan Mas Husein. Mungkin ia sendiri geli dengan panggilan ”Mas” itu. Tapi, di desa kami tidak ada panggilan Kak atau Kakak. Mau dipanggil Pa’, ia masih sangat muda. Baru kelak, di tahun 2022, saya tahu panggilan Mas itu seharusnya ”Kiai”. Mas Husein seharusnya Kiai Husein. Di Jawa, kiai adalah panggilan tokoh agama yang jadi imam di masjid, bukan kakak. Mbak Sofwati jarang pulang. Dia kuliah di IKIP Malang. Entah jurusan apa. Saya hanya bertiga di rumah: bapak, saya, dan Udin –adik bungsu saya. Ibu sudah lama meninggal. Kakak sulung, Mbak Khosiyatun, sudah lama pula merantau ke Samarinda. Saya belum paham apa itu pembaharuan pemikiran Islam. Yang saya tahu, kakak saya itu pintar sekali. Kalau debat, tidak mau kalah. Ia seperti Srikandi. Tangkas sekali. Pemberani. Roknya paling pendek di antara orang di desa –kalau lagi pulang. Ketika masih SMA (Muallimat) seragam sekolahnya kebaya, jarit, dan kerudung –yang kerudungnyi lebih sering jatuh ke pundak. Yang saya benci padanyi: dia tidak mau ber-boso kromo inggil pada ayah. Kromo biasa pun tidak mau. Kalau bicara dengan ayah, dia selalu pakai bahasa ngoko –seperti bicara pada teman. Itu tercela di desa kami. Kakak tidak peduli. Saya juga tidak suka ini: waktu saya pulang dari mondok sebulan di Kaliwungu, dekat Semarang, ia memeriksa kitab kuning yang saya bawa pulang. ”Isi semua kitab ini bisa kamu pahami hanya dalam satu minggu kalau bukunya berbahasa Indonesia,” katanyi. Saya tidak pernah lupa kata-katanyi itu. Tidak banyak lagi yang saya tahu tentang kakak saya itu. Begitu jarang bertemu. Saya asyik dengan masa kanak-kanak saya sendiri: sebagai penggembala kambing. Begitu tamat madrasah aliyah (setingkat SMA), saya menyusul kakak sulung ke Samarinda. Putuslah hubungan dengan kakak kedua itu. Dari kakak sulung saya mendengar Mbak Sofwati kawin dengan Mas Husein. Di Samarinda saya kian terlibat di organisasi ekstrakampus. Ups, tidak saya sangka kakak kirim dokumen tebal lewat pos. Tumben. Saya buka kiriman itu. Isinya: materi pendidikan yang baru dia ikuti: pendidikan pers Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI). Saya disuruh masuk IPMI. Diam-diam saya memang mengagumi kecerdasan dan keaktifan kakak saya itu. Saya pun bergabung ke IPMI. Lalu, magang di media milik aktivis IPMI Samarinda, Alwi Alaydrus–sekarang jadi ulama di Kaltim. Suatu saat saya naik kapal laut: ikut pendidikan aktivis di Jawa. Sekalian mampir kampung, satu hari. Kakak senang saya menuruti keinginannyi masuk IPMI. Apalagi, sudah magang di Mimbar Masyarakat Samarinda. Kakak ternyata sudah punya anak: satu, laki-laki. Namanya Andi. Saya gendongia. Saya ajak main ia. Hanya satu hari. Saya juga bertemu Mas Husein. Masih juga selalu membawa badik. Saya pun kembali ke Samarinda. Putus hubungan lagi. Kelak, dari kakak sulung saya dengar: Mas Husein diangkat jadi pegawai negeri dengan tempat tugas di Jambi. Mbak Sofwati ditinggal dulu di Madiun –belum bisa ikut pindah karena terikat sebagai guru agama di SDN negeri di Madiun. Dari kakak sulung pula saya mendengar Mbak Sofwati meninggal dunia. Di Jambi. Kabar duka itu baru sampai ke Samarinda hampir sebulan kemudian. Surat lewat pos adalah satu-satunya alat komunikasi saat itu. Sebenarnya ada juga telegram. Yang bisa sampai dalam sehari. Tapi, saya tidak tahu mengapa hanya disampaikan lewat surat. Kalau pun ditelegram, toh tidak ada yang bisa melayat ke Jambi. Kelak, lebih 30 tahun kemudian, saya ke Jambi. Bikin perusahaan di Jambi. Kepada teman-teman di Jambi saya ceritakan: saya punya kakak yang dimakamkan di Jambi. Tapi, saya tidak tahu di mana. ”Suaminyi bernama Husein Roni. Pegawai kantor agama,” kata saya. Tidak ada informasi lain lebih dari itu. Ajaib. Teman-teman bisa menemukan makam kakak saya: di pinggir jalan besar menuju ke Bandara Jambi. Dalam kunjungan berikutnya ke Jambi, saya ziarah ke makam kakak saya itu. Mas Husein sendiri –minggu lalu saya baru tahu– tidak lama di Jambi. Setelah kakak meninggal, ia minta pindah tugas ke kampung halamannya di OKU. Ia pulang kampung dengan anak tunggalnya yang baru berumur 3 tahun. Sampai puluhan tahun berikutnya, kami tidak berhubungan lagi dengan Mas Husein. Dari Dik Udin, saya dengar Andi menghilang dari rumah orang tua di OKU. Adik saya tahu itu. Mas Husein menghubungi adik: apakah Andi yang masih remaja kecil itu lari ke Magetan. Tidak. Pekan lalu, ketika saya diundang makan malam di rumah bupati OKU, saya kaget. Senang. Seorang staf protokol bupati berbisik ke saya: ”Pak Husein, ipar bapak, mau bertemu.” ”Anda tahu beliau? Tinggal di kota ini?” tanya saya. ”Beliau di Simpang Duo, Kabupaten OKU Selatan. Tapi, hanya dua jam dari Baturaja ini. Asal bisa bertemu, beliau mau berangkat ke sini,” katanya. Tentu saya mau sekali. Apalagi, putri beliau, dari istri sambungan, tinggal di Baturaja. Keesokan paginya, seusai senam dan kuliah umum di Universitas Mahakarya, saya ke rumah putri Mas Husein itu. Beliau sudah di rumah itu. Menyambut saya di halaman. Sebenarnya saya agak pangling dengan beliau. Tapi, dari postur tubuhnya, saya yakin itulah Mas Husein yang muda dulu. Saya peluk ia. Erat sekali. Lama sekali. Mas Husein kini sudah berumur 76 tahun. Sudah lama pensiun. Tinggal di desa kelahiran di Jagaraga. Punya kebun karet. Ladang jagung. Jadi pemuka agama. Dari cerita beliaulah saya baru tahu masa-masa akhir hidup kakak saya. Inilah ceritanya: Setelah delapan bulan ditinggal ke Jambi, kakak berhasil mengurus surat pindah ke Jambi. Dari Madiun, kakak naik bus ke Jakarta. Lalu, naik bus lagi ke Lampung. Dari Lampung, naik bus lagi ke Martapura (kini masuk Kabupaten OKU Timur). Dari Martapura, kakak naik kendaraan umum ke Simpang Duo. Lalu, ke Jagaraga. Ke mertua. Itulah kali pertama kakak ke rumah mertua. Sambil membawa cucu. Dari Jagaraga, kakak ke Palembang. Lalu, ke Jambi, menyusul suami. Di Jambi kakak mengajar agama di salah satu SD. Mas Husein bekerja di Kantor Agama Kota Jambi. Ternyata baru sebulan di Jambi, kakak sakit. ”Sakit maag,” ujar Mas Husein. Saya pun bertanya lebih detail tentang sakitnyi kakak. Mas Husein tidak terlalu tahu soal penyakit. Semua terserah dokter. Yang jelas, kakak dimasukkan rumah sakit. Sampai satu bulan. Muntah darah. Lalu meninggal. Berarti, hanya dua bulan kakak hidup di Jambi –itu pun yang sebulan di rumah sakit. Dari muntah darahnyi itu saya berkesimpulan: kakak sakit liver. Persis seperti yang saya alami di kemudian hari. Saya bisa membayangkan betapa kakak harus menyesuaikan diri hidup di Jambi. Dari seorang aktivis yang sangat ”kosmopolit”, menjadi guru SD di Jambi. Dari Mas Husein pula, minggu lalu itu, saya bisa mendapat dua foto lama kakak saya. Begitu lama saya memandangi foto itu.(Dahlan Iskan) Anda bisa menanggapi tulisan Dahlan Iskan dengan berkomentar http://disway.id/. Setiap hari Dahlan Iskan akan memilih langsung komentar terbaik untuk ditampilkan di Disway.
Sumber: